Membumikan Wayang, Mengangkat Jagad Pewayangan pada Tataran yang Baru
by admin|| 31 Oktober 2017 || 8.483 kali

Menurut rekam jejak sejarah mengenai pakem pedalangan dari sejumlah pengamat dan penulis, dibeberkan kiprah Ki Nartasabdha (1925−1985) sebagai dhalang yang pertama melakukan semacam upaya membumikan wayang (desakralisasi dan dekonstruksi pakem pedhalangan). Dengan demikian, pakem dipandang ibarat buku tuntunan bagi para siswa atau pemula yang ingin menjadi dhalang. Berbekal keahlian dan daya cipta, dhalang dapat menafsirkan kembali pakem sesuai dengan perkembangan zaman.
Gaya pakeliran Ki Nartasabdha pada awal kiprahnya sebagai dhalang, masih lekat dengan pakem gaya Surakarta. Sejak 1958, ia merintis penghubung pakeliran gaya Surakarta dengan Yogyakarta, misalnya dalam jenis sulukan, gendhing, dan keprakan. Demikian pula gendhing-gendhing dan garap karawitan dari daerah lain, seperti Jawa Timuran, Banyumasan, Pasundan, dan Bali, bahkan merambah pada idiom-idiom gendhing bedhayan, musik keroncong, langgam Jawa, sampai musik pop dangdut. Janturan yang digunakan pun diluar kebiasaan atau tidak lazim, dan perwatakan tokoh-tokoh dengan penekanan pada sisi kemanusiaannya.
Kemampuan Ki Nartasabdha menjabarkan lakon baku dan carangan melalui penggarapan sanggit dan pemusatan ekspresi dalam dialog wayang (antawacana), dinilai kalangan pedhalangan dan masyarakat pecinta wayang, merupakan sesuatu yang baru dalam dramatisasi pakeliran. Dalam hal lakon pun, ia yang pertama kali membuat lakon banjaran (biografi tokoh pewayangan), misalnya Banjaran Bisma, Banjaran Karna, Banjaran Bima, Banjaran Arjuna, dan Banjaran Gathutkaca. Ia juga menggubah lakon-lakon yang tidak lazim dipergelarkan dalam pakeliran wayang kulit purwa, seperti lakon Sakuntala, Sawitri, dan Damayanti.
Perubahan pakeliran yang dilakukan Ki Nartasabdha, dipandang sebagai garap pakeliran secara seimbang (ora bot sih) dengan empat hal, yaitu moral, peribadatan, keindahan seni, dan hiburan. Pembaharuan pada pengaturan panggung juga telah melahirkan seni pedhalangan yang disebut pengamat sebagai gaya Nartasabdha (Nartasabdhan).
Ki Cerma Suteja sebagai salah satu dwija (guru) di Habirandha (Sekolah Pedhalangan Kraton Yogyakarta, Hanganaake Biwara Rancangan Dhalang) mengemukakan bahwa seni pedalangan dari generasi ke generasi senantiasa mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan zaman, manut zaman kelakone, dan punya kekhasan tersendiri. Sangat mungkin terjadi bahwa penerapan pakem pakeliran selalu berkembang mengikuti zamannya.
Mengenai gagrak (gaya), dikemukakan Ki Edi Suwanda, seniman pedalangan dari Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa jenis-jenisnya memang ada yang mirip-mirip atau sama, namun masing-masing punya pakemnya sendiri-sendiri, baik ringgit, iringan, maupun lampahan. Meskipun demikian, diingatkan Ki Edi, perbedaan ini tidak perlu sampai membuat tersesat dan terpecah-belah, karena secara akademis, merupakan acuan atau pedoman yang saling melengkapi. Dampak munculnya gejala sosial politik dan perubahan zaman, sangat berpengaruh terhadap kebudayaan bangsa. Karena itu, Ki Edi merasa senang dan berterima kasih atas perhatian pihak-pihak yang tetap peduli pada pewayangan.
Baiknya dulu itu tidak sama dengan baiknya sekarang, ungkap Trisno Santoso, dari jurusan pewayangan ISI Surakarta, karena berkesenian itu selalu berkembang. Trampilnya dalang sabet masa Ki Cerma Krusuk, Ki Sugi Hadi Karsana, Ki Timbul Hadiprayitna, Ki Hadi Sugita, Ki Suyatin, Ki Suparman Cermawiyata, Ki Ganda Margana, Ki Sugita, dan Ki Sugati, sudah berbeda dengan masa Ki Sutana, Ki Sutikna, Ki Suteja, Ki Sukaca, Ki Sudiyana, Ki Sumana, dan berbeda lagi dengan masa Ki Sena Nugraha, Ki Benyek, Ki Suharna, Ki Bambang, dan lain-lain.
Demikian juga cara dalam menghadapi teknik. Dalang pada zaman dulu, mematahkan gapit wayang itu dianggap tabu; lampu mati saat pertunjukan itu menjadi perbincangan; ketika mendalang, ada bayi lahir di lingkungannya, itu menjadi anak sampir dalang.
Dulu, masih banyak dalang yang meruwat anak ontang-anting, uger-uger lawang, kembang sepasang, gedana-gedini dan lain-lain. Masih banyak pula anak yang dibesarkan dengan sajen ruwatan dan sajen wayangan, ayam panggang sajen, ingkung sajen dan lain sebagainya. Di rumah simbah, ada merpati, ayam, angsa, kutut, derkuku, mentog untuk sajen ruwatan.
Suasana pakeliran pada 1970-an dan 1980-an, dijejali dengan humor yang kurang pas, dari dhalang-dhalang yang ingin mengikuti keberhasilan Ki Nartasabdha, namun hanya meniru humor (banyolan). Pakeliran (sebagai wadah) menjadi tidak sesuai dengan pesan pokok yang hendak disampaikan (isinya). Keadaan ini dinilai Gendhon Sedyono Djojokartika Humardani (1923−1983), ketua Pusat Kesenian Jawa Tengah (1969-1983), dan ketua Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta (1975−1983), sangat mengkhawatirkan, dan membuat jagad pakeliran mengalami proses pendangkalan mutu yang parah (kronis). Hal ini pun memrihatinkan kalangan pengamat seni pedhalangan, karena tidak seimbangnya aspek yang bersifat pokok dengan yang bersifat teknis.
Karena itu, Humardani menggagas pakeliran padat, yang mengutamakan perpaduan ’wadah’ dan ’isi’ pakeliran. Meskipun demikian, bukan untuk menggeser kedudukan pakeliran semalam suntuk, melainkan untuk memperkaya kehidupan budaya, dan tidak menghilangkan pakemnya, namun mengurangi lama pentasnya. Sejak 1977, pakeliran padat disebarkan di seluruh Jawa Tengah melalui penataran-penataran dalang, sarasehan, lokakarya, lomba naskah, lomba penyajian pakeliran padat, serta siaran radio dan televisi, kepada kalangan pedhalangan, budayawan, dan masyarakat pecinta wayang.
Sepeninggal Ki Nartasabdha, pemrakarsa pembaruan pakeliran, dan Gendhon Sedyono Djojokartika Humardani, penggagas pakeliran padat, Ki Manteb Soedharsono melanjutkan perjuangan mereka, dengan tetap mengusung semangat pembaruan, menambah unsur laga dalam pergelaran wayang kulit purwa. Ketrampilannya menggerakkan wayang (sabetan) sangat cepat, sehingga dijuluki para penggemarnya sebagai dalang setan. Pakeliran menjadi gegap-gumpita dalam perkembangan zaman. Meskipun demikian, Ki Manteb menyadari bahwa setiap dalang memiliki corak gaya sendiri-sendiri yang tentu berbeda-beda.
Hal yang memengaruhi penampilan Ki Manteb secara teknis dan artistik adalah kemampuannya membuat wayang, menatah, mewarnai, dan memperbaiki wayang, yang sudah ditekuni sejak masih anak-anak. Ki Manteb bahkan terus belajar, membaca buku-buku, dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh. Meskipun sudah mantap sebagai dhalang yang mumpuni, Ki Manteb tidak segan-segan berbagi pengalaman dengan para dalang muda, dan memberi dorongan bahwa seorang dalang harus pandai membuat sanggit, mengetahui suasana politik, masyarakat, dan keadaan zaman.
Seperti lakon cerita wayang yang penuh drama, menurut Trisno Santoso, dunia dalang pun menawarkan pemecahan terhadap penyelesaian pertikaian, dan yang pasti, masing-masing dalang punya pandangan sendiri-sendiri. Inilah sebenarnya yang menjadi kekayaan dalam dunia pedalangan. Dulu, pedalangan itu bersumber dari satu (karaton). Dibaginya Kerajaan Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta, membawa dua gaya besar dan terpenting dalam tradisi dalang. Setelah karaton menjadi dua, kemudian muncul sejumlah gaya. Kini, ada gejala untuk menyatukan kembali gaya itu.(hen/ppsf)
Berita Terpopuler

Siklus Air: Definisi, Proses, dan Jenis Siklus Air
by museum || 04 Juli 2023
Air merupakan salah satu sumber daya alam yang diperlukan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Untungnya, air adalah sumber daya alam terbarukan. Proses pembaharuan air berlangsung dalam ...
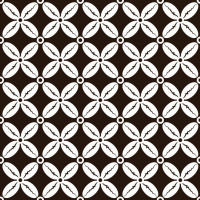
Batik Kawung
by museum || 02 Juni 2022
Batik merupakan karya bangsa Indonesia yang terdiri dari perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia, yang membuat batik memiliki daya tarik adalah karena batik memiliki corak ...

Pahlawan Perintis Pendidikan Perempuan Jawa Barat Raden Dewi Sartika (1884-1947)
by museum || 24 Mei 2022
Raden Dewi Sartika dilahirkan tanggal 4 Desember 1884 di Cilengka, Jawa Barat, puteri Raden Somanagara dari ibu Raden Ayu Rajapermas. Dewi Sartika menumpuh Pendidikan di Cicalengka. Di sekolah ia ...

Limbah Industri: Jenis, Bahaya dan Pengelolaan Limbah
by museum || 18 September 2023
Limbah merupakan masalah besar yang dirasakan di hampir setiap negara. Jumlah limbah akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Permasalahan sampah timbul dari berbagai sektor terutama dari ...

Raden Ayu Lasminingrat Tokoh Intelektual Pertama
by museum || 24 Oktober 2022
Raden Ayu Lasminingrat terlahir dengan nama Soehara pada than 1843, merupakan putri seorang Ulama/Kyai, Penghulu Limbangan dan Sastrawan Sunda, Raden Haji Muhamad Musa dengan Raden Ayu Ria. Lasmi ...
Berita Terkait

Inilah Sabda Tama Sultan HB X
by admin || 11 Mei 2012
YOGYA (KRjogja.com) - Sabda tama yang disampaikan oleh Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan HB, secara lugas menegaskan akan posisi tawar Kraton dan Pakualaman dalam NKRI. Sabda tama ini ...

Permasalahan Pakualaman Juga Persoalan Kraton
by admin || 11 Mei 2012
YOGYA (KRjogja.com) - Kerabat Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, KRT Hadi Jatiningrat menafsirkan sabda tama Sri Sultan Hamengku Buwono X, sebagai bentuk penegasan bahwa persoalan yang menyangkut ...

PENTAS TEATER 'GUNDALA GAWAT'
by admin || 18 Juni 2013
"SIFAT petir itu muncul secara spontan, mendadak, tidak memilih sasaran. Beda dengan petir yang di lapas Cebongan. Sistemik, terkendali," ujar Pak Petir.Pernyataan tersebut lalu dikomentari super ...